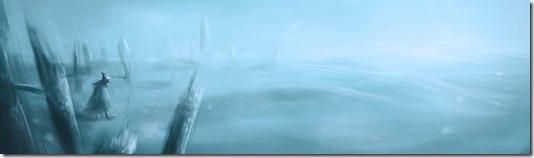Satu lagi cerita tentang “Salahnya yang diam satu, salahnya yang ngomong seribu.”
Jadi beberapa bulan yang lalu Yaya patah hati. Alasannya klise banget: Pacarnya pacaran lagi sama orang lain. Tanpa pengumuman.
Tipikal gaya Virgo mengamuk adalah diam seribu-satu bahasa. Pada awalnya, at least. Jadi, begitu tahu pacarnya sudah buka cabang di lain hati, Yaya langsung masuk kepompong hening. Diam sediam-diamnya. Tak berbunyi di twitter, Facebook apalagi temu langsung.
Selama diamnya itu, Yaya naik gunung, retret meditasi. Tahu dong seperti apa retret-retret gila itu. Yang tadinya masih komunikasi verbal sama orang rumah, di gunung tidak komunikasi sama sekali dengan siapapun. Seperti zombie tapi masih makan & mandi.
Dan karena diam, semua tenaga pikirannya menyatu. Bawah sadarnya meruah. Pacarnya yang bikin sakit hati itu dimutilasi berkali-kali dalam bayangan.
Tapi brutalitasnya cuma sampai pikiran saja. Sumpah. Karena begitu turun dari gunung, Yaya ceria kembali; akselerator bahasanya dibablasi, dan banyak yang tersinggung karenanya. Tapi bukan itu inti ceritanya.
Pada saat-saat galaunya kambuh, Yaya menggerataki linimasa mantannya yang membuatnya begitu brutal dalam hening. Salah satu update statusnya tentang sakit punggung. Punggung? Bukannya itu bagian paling sering yang Yaya potong-potong dalam bayangannya selama puasa bahasa dan angkara murka?
Mungkinkah?
*
Waktu Kanjeng Nabi bilang “Jangan marah”, ada banyak alasan terselubung dalam titahnya. Orang yang diam bukannya lemah. Apalagi saat marah. Khususnya yang sedang marah.
Mau percaya atau tidak, ada yang kekuatan laten yang menumpuk dari emosi yang dibendung. Karya seni, misalnya, butuh fermentasi agar matang. Juga zaman dulu, para Resi dan Wali sering bertapa di hutan untuk menajamkan indera dan kekuatan.
Diam, baik sehari atau sesaat, juga begitu.
*
Lanjut cerita tadi, ya? Kasihan dong tuh mantan cuma diceritakan sampai punggungnya kecekit. Apa tak ada happy ending baginya? Biar kata dia kunyuk, masih karya Tuhan, kan?
Beberapa hari yang lalu, si kunyuk mantan menelepon selagi Yaya masih di ambang galau: Belum sarapan, masih mengantuk dan rada horny. Dari percakapan itu, emosi Yaya terpancing; segala sumpah serapah yang dipendamnya selama beberapa bulan terakhir meluncur deras dari mulutnya.
Lelaki itu bukannya terpekur memikirkan kesalahannya malah tertawa-tawa kesenangan. Sakit punggung dan galaunya sembuh total saat mendengar Yaya tak kuasa menahan marah, bok.
Sementara Yaya? Haha.
Setelah berhasil membungkam mulutnya dengan kepalan tangan dan selusin kaus kaki, akhirnya tertawa juga. "Ya sudahlah, biarlah kampret itu sembuh dan tertawa lagi. Mungkin memang masa hukumannya sudah selesai, dan sudah waktunya ia dimaafkan. Semoga pacar barunya lebih erat mengendalikan mulut dan mampu menyiksanya lebih lama. Amin.”