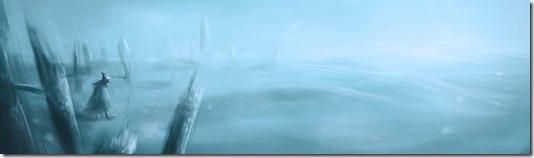Seorang guru mengaji datang ke Kyai, “Gaji kula sebulan empat puluh ribu.”
Untuk ilustrasi – bukan mengumpan kasihan – pak Guru bercerita tentang celananya yang semata wayang. Celana itu selalu bau dan lepek karena hanya dijemur antara jam mengajar. Pak Guru bukannya jorok, tapi kebersihan celananya kalah penting dibanding anak dan istri yang harus makan.
Sabun mahal.
Kata Kyai, “Jadi, sampeyan maunya bagaimana?”
“Mohon restunya, Pak Kyai, kula mau merantau ke Jakarta, jadi tukang ojek.”
“Setelah jadi tukang ojek, apa lalu akan menjadi kaya? Bukan cuma sampeyan saja yang akan tetap miskin, tapi juga semua anak yang mengikuti contoh gurunya.”
Pak Guru diam. Harapannya hangus, hatinya kecewa, dan idealisme Kyai ini menyebalkan.
“Pulanglah” kata Kyai, “jangan berkecil hati, dan yakini ilmu yang sampeyan ajarkan. Tuhan tak Alpa, tapi doyan mencoba. Kekayaan duniawi takkan berarti tanpa tabungan yang cukup untuk akhirat.”
Mungkin saat itu pak Guru merutuk dalam hati, “Gimana mau memikirkan akhirat, wong bertahan hidup saja susah.”
Beberapa bulan kemudian, pak Guru kembali. Katanya, “Alhamdulillah, pak Kyai, mertua saya meninggal.”
“Mertua meninggal kok disyukuri?”
“Bukannya mensyukuri mertua meninggal, tapi warisannya. Kula kebagian sawah setengah bahu.”
Kata Kyai, “Untung sampeyan tidak jadi mengojek kan? Bisa-bisa mertua sampeyan tidak jadi meninggal.”
Mungkin hidup memang cuma sekejap, menjalankannya saja yang susah. Mungkin bersabar memang lebih berat daripada mengarang ngawur.
Siapa tahu besok…
Catatan Kaki: Pernah dititipkan di lain blog.