- Default Live Writer Image Placement
- Default Live Writer Album Placement
- Additional Polaroid Plug-in
Angsar (Jawa): Daya kesaktian sebuah benda. Bisa baik, bisa buruk. Tergantung yang memegang.

Uang itu dibawa ke kyainya. “Tolong sampaikan pada orang-orang di Mekkah untuk menunaikan haji atasnama almarhum ayah saya.”
Haji ini namanya Haji Badal. Badal artinya subtitut/pengganti. Jika pahala yang menghajikan adalah uang badal yang diterimanya, pahala yang dihajikan adalah kesejahteraan di alam sana. Lalu apa pahala yang telah membecak selama dua tahun?
Logika langsung protes. Daripada uang sebanyak itu buat menghajikan orang yang sudah tidak butuh makan, minum dan merokok, kenapa tidak dibelikan buku, bata, atau beras? Kenapa malah dihamburkan tak berbekas?
Apa jaminannya di alam sana arwah bakalan lebih sejahtera dengan haji badal? Apa jaminannya Tuhan masih ada?
*****
Waktu orang-orang di Mekkah ditawarkan proyek haji badal ini, mereka nanya, “Untuk siapa? Uangnya halal apa tidak?” (Karena syaratnya haji adalah kemampuan. Maka uang yang dipakai untuk haji akan diaudit perjalanan: uang bersih meringankan, uang takjelas memberatkan.)
Uang itu dekil dan bau; endapan keringat membecak selama dua tahun. Bukannya diterima, mereka malah tersindir. “Halah, cuma duit segitu. Dibayar atau tidak, selagi kita masih melayani tamuNya, kita bakal terseret arus musimnya. Sekalian ihram dan niat tak akan memengaruhi. Kembalikan uang ini ke Jawa, biar hajinya dibayar dari ikhlas kami.”
*****
Ada yang bilang, uang halal tak kemana. Mungkin saking uang itu halal (juga bau dan dekil) sampai ditolak semua tangan.
Jika dikembalikan ke tukang becak tadi, kita seperti melecehkan usaha dan ikhlasannya. Dipaksakan ke tangan penghaji badal, kita meremehkan keikhlasan mereka juga.
Jadi?
Uang itu dibangunkan mesjid. Klise, tapi tak mengapa. Mesjid itu besok akan mengumpulkan umat yang masih mau mengaji dan sembahyang. Umat yang mengaji nantinya akan ada lagi yang seperti tukang becak tadi: kerja untuk mengumpulkan uang halal, daripada merampok atau meminta.
*****
Klise, tapi tak mengapa.
Lepas dari adanya hidup setelah mati apa tidak, lepas dari adatidaknya kesejahteraan di alam sana, bukankah badal surga di dunia adalah kebahagiaan yang lebih-kekal? Adakah badal kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sebaik sejahtera sehari-hari? Tidakkah badal itu cukup bagi seorang tukang becak, maupun hartawan, untuk terus memeras peluhnya, sebaik-baiknya?
Karena jika bukan hati yang lega, tidur yang lelap, perut yang terisi, badal apa lagi kita membuat kita ikhlas mendayung, memacul dan melangkah, meski kehujanan, kemacetan dan kebanjiran setiap hari?
Semoga peluhmu menyejukkan hatimu dan mereka yang di sekitarmu, setiap hari.
Amin.
"There are certain periods in the life of man when Fate seems to have done her worst, and any further misfortunes which may befall are accepted with a philosophical resignation, begotten by the very severity of previous trials."
Pluralisme membuat semua gerakan jadi lambat.
Rasanya pluralisme memaksa jeda berpikir sebelum sempat bereaksi: kenapa ya begitu? Apa tafsirnya di Kitab-kitab? Apa tafsirnya tembus masa?
…karena ketika fakta mulai membulat, ketika faham mulai menjalar, biarpun sekilas tanpa seluruh, semuanya jadi lebih sedih. Bukan muram durja, bukan gelap indera atau ungu raung. Tapi sendu haru. Seakan pengertian datangnya hanya dari sedih yang tenang. Seperti nasihat yang diam.
Adakah nabi dan cinta agung dan raja adil yang tak sepi sendu?
Teori Film Kehidupan
Daddy pungut pernah bilang, hidup manusia seperti filem bioskop. Kita yang menjalankan sekedar aktor pasif kehidupan masing-masing. Ga ada yang bisa dirubah. Begitu kita lahir, rol film itu udah selesai disutradarai, diproduksi, diedit, ditulis dan disegel disana-sini.
Kalau beruntung, kita bisa belajar untuk menikmati jalannya film kehidupan masing-masing. Kalau tidak, ya, sama saja. Filem itu tidak akan berubah.
=====
Contoh Kasus Film Kehidupan yang Nyangkut
Aku punya teman dari SMA. Warga negara Amerika yang untuk satu alasan maupun lainnya, nyangkut di Jeddah. Pikirkan variable kehidupannya: lelaki, warga negara Adikuasa, tapi ga bisa ambil keuntungan dari kewarganegaraannya. Ga bisa balik ke negrinya. Ga bisa menikah atau punya paspor baru. Ga bisa menyelesaikan IGCSE. Apalagi kuliah atau menekuni cita-cita. Dia seperti nggak ada di peta kewarganegaraan.
Cuma dua tahun di bawahku, tapi secara legal, profesional dan akademis nyangkut (mungkin untuk selamanya) di umur 18 tahun.
Ga kebayang berapa ratus mimpinya yang telah hinggap terus terbang ga berbekas. Ga kebayang apa rasanya jadi orang dalam posisinya. Memainkan filem kehidupan sepertinya.
Hebatnya, dia tetap baik, man. Dia tetap bakti sama orangtuanya. Dia tetap sayang sama adik-adiknya. Dia tetap sabar. Ga marah-marah. Aku ga pernah ngeliat dia kecuali dengan wajahnya yang paling hangat, paling bersahabat sama semua orang. Jangankan ngeliat mukanya, bahasa verbalnya aja halus dan sopan. Tipikal orang Amerika yang tumbuh di lingkungan berpendidikan. Cuma nyangkut di dunia yang tak mengakuinya.
Aku salut.
=======
Mungkin pilihan hidup kita cuma segitu: sekedar memilih untuk mau terima apa tidak.
Kalau mau terima, ya mungkin kerut-kerut di wajah akan berkurang, cahaya kehidupan lebih terang, dan orang lain akan lebih sayang. Sampai mati, orang-orang seperti temanku akan selalu dicintai orang. Bukan karena dia sukses atau gagal, bukan karena dia WNA atau PhD. Atau makna film hidupnya dapat kita mengerti.
Kalau tidak mau terima juga bisa, silahkan jegal kanan-kiri, silahkan menuntut yang lebih baik, sampai akhirnya kembali menyadari, Tuhan kita ga bisa diganti, dan kalimatNya adalah Yang Terjadi.
Dari mana kita tahu bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini berupa keberhasilan atau kegagalan? Bagaimana kita tahu bahwa filem kehidupan emang semestinya begini atau begitu?
Karena, pada akhirnya, mungkin perjuangan hidup kita semua adalah menerima apa yang sudah pasti. Berani mengiyakan pertanyaan ini: "Masak cuma segini?"
Kalau iri hati adalah dosa, apalagi cemburu. Kita cemburu karena takut kehilangan, takut kekurangan dan takut tak kebagian.
Cemburu dan iri kembar rasa. Bedanya, cemburu muncul dari ancaman pihak ketiga. Mottonya cemburu mungkin begini: "Kamu tidak boleh bahagia kecuali bersamaku." Sementara motonya iri lebih sederhana: Aku mau milikmu.
Herannya, di Timur Tengah cemburu adalah sikap ksatria.
Di padang pasir, orang yang mencemburui pasangan dan keluarganya adalah orang-orang yang jauh dari sikap Dayyuthi: mirip babi yang tidak peduli pasangannya disetubuhi siapa.
Saking bebasnya lelaki Arab mencemburui perempuannya, sampai ditutupi seprai sepanjang hidupnya.
Kalau dipikirin, babi tidak merasa cemburu karena bisa makan apa saja. Anaknya banyak. Hidup enak. Mau ngapain cemburu?
Karena di Arab sumberdaya kehidupan susah direbut dicari, maka wajarlah cemburu dianggap sikap ksatria dan kode moral yang menjaga kelangsungan hidup di sana.
Tapi di sini? Di negri di mana perempuan dan lelaki bisa sama-sama cari makan, beli rumah, jadi manusia seutuhnya. Di negri di mana sumber daya kehidupan hampir tumpah ruah. Di negeri yang rakyatnya buanyak bnuanget. Apa masih perlu kita menghalalkan cemburu?
Kecuali teman kita sedikit, penggemar kita jarang, dan pergaulan kita dangkal, apa masih perlu kita merasa cemburu? Apa salahnya orang lain kalau sikap sosial kita kita yang katro?
Karena cemburu disebabkan hati yang miskin, maka obatnya juga dengan pengayaan hati. Ga pernah liat pastor atau bikkhu atau psikoterapis yang nyuruh umatnya untuk bebas bercemburu, kan?
Dalam tradisi Islam, waktu ada sahabat yang (saking cemburunya) ga ngizinin saudarinya menikah, Kanjeng Nabi bilang, "kalau kamu cemburu, Allah lebih mencemburui mereka."
Karena yang sebenarnya punya hak untuk mencemburui kita (sekaligus sumbernya semua obat) cuma Tuhan: Dia Pemilik Cipta, dari Awal sampai Akhir.
Kita semua ada jodohnya masing-masing, Seandainya jodoh sudah selesai, mau dicemburui sampai kiamatpun, apa yang dipisahkan Tuhan tak dapat disatukan cemburu.
Beruntunglah mereka yang hatinya cukup lapang untuk memuat Tuhannya; sampai matipun tak akan kesepian, apalagi kekurangan teman.
Beruntunglah mereka yang bahagia dengan apa yang telah ditetapkan, nyata atau tak kasat mata; karena hati yang kaya tak butuh ditambal janji, bukti atau benda. Amin.
Negeri ini penuh berkah. Semua orang bisa makan, asal mau nyari. Asal mau melangkahkan kaki. Mungkin karena rakyatnya banyak, mungkin karena ummatnya taat, jadi Tuhannya murah rahmat.
Aku pernah lihat orang jalan kaki bawa alat pengukur tensi dan timbangan pijak. Biarpun pelanggannya tukang ojek & mbok jamu dan teori medisnya serabutan tapi rejekinya halal. Dia nggak nyolong, kan?
Pernah sekali lagi lihat ibu-ibu sepuh mendorong gerobak, jualannya pecel. Nggak tahu penglaris apa yang dipasangnya, tapi pelanggannya banyak. Aku menikmati takjub sambil berdiri menunggu giliran dilayani.
Sekali lagi, pernah duduk di sebelah pemuda tanggung, umurnya baru 19 tahun, pendidikannya cuma sampai kelas 5 SD, tapi sudah biasa bolak-balik Brebes-Jakarta untuk memenuhi order rambut extension. Dia punya pelanggan tetap. Dia punya tabungan. Aku salut padanya; waktu umur 19 tahun, aku lagi marah-marahnya ama uang saku yang cuma USD300/bulan.
Paling sering liat anak kecil yang (dengan modal tepuk tangan & nyanyi sumbang aja) udah bisa bikin duit di pinggir jalan. Kupikir, mungkin saking berkahnya negeri ini, sampai tepuk tangan aja bisa dijadikan modal. Asal mau tepuk tangan. Asal mau usaha.
Kalau dipikirin, jangankan manusia yang diberi tangan dan kaki dan otak. Kucing & semut & rumput aja ada rezekinya. Apalagi manusia. Apalagi manusia yang mau usaha.
Kalau dipikirin, dimana-mana cari uang susah. (Cari uang yang gampang namanya nyupang.) Tapi kalau maling & tukang santet aja ada rezekinya, apalagi pemilik niat baik. Apalagi tangan dan mulut yang baik. Apalagi yang jujur. Apalagi yang bersyukur.
Makanya jangan kuatir, semua ada bagiannya. Jangan putus asa. Jangan mengeluh. Keluarlah dan cari rezekimu. Rejekimu nggak akan kemana-mana, nungguin kamu menjemputnya.
Marah adalah satu dari ketujuh Dosa Mematikan di agama Kristen. Salah satu sumber kesengsaraan di agama Buddha. Dan di agama Islam, Kanjeng Nabi pernah ngewanti-wanti orang, "Apapun yang terjadi, jangan marah, jangan marah, jangan marah."
Serius nih, apa salahnya orang marah?
Marah = Nafsu
Kanjeng Nabi ga ngebahas lebih jauh, ga ngebilangin jenis-jenis marahnya orang. Mungkin karena semua orang kalau marah sama: rentan nafsu. Orang kalau marah, nafsu ngomongnya, nafsu makan, minum, memukul, nafsu menyebadani pacarnya jadi lebih kenceng, atau nafsu beres-beres rumah.
(Anger burns all clean. - Maya Angelou)
Marah = Ga enak
Yang pasti, semua orang akan berusaha menetralisir marah. Karena marah adalah rasa yang nggak enak. Bikin cepat tua karena merengut. Bikin hangus, karena marah adalah energi panas.
Dan yang bikin kanjeng nabi ngewanti-wanti kita tentang kemarahan karena kita jadi lebih rentan & lemah saat marah. Saking terkikis kemuliaan kita sebagai manusia saat tergoda nafsu untuk menghilangkan rasa marah yang ga enak itu.
Pernah liat orang marah? Ada yang menetralisir sakit hati dengan memaki, teriak-teriak, olahraga, kerja lebih giat, atau diam seribusatu bahasa.
Marah = Telanjang
Aslinya orang ketahuan kalau lagi marah. Kita bisa tahu kualitasnya orang, baik buruk hatinya saat dia marah.
Karena kemarahan adalah penelanjangan hati kita. Yang hatinya bersih, marahnya dengan sayang: kritik konstruktif, menjaga mulut, merubah sikap tanpa merusak. Yang hatinya belum beres. yah, yang ini sih udah banyak contohnya: bocor dengan gosip, rebutan harta, teriak-teriak ego: ini milikku, itu hakku, ini aku-aku-aku.
Marahlah Dengan Baik
Apapun metodenya, barometer sehat-tidaknya cara orang menangani nafsu marahnya adalah "seberapa jauh nafsu itu menguasainya akal sehatnya". Yang melepas marahnya dengan olahraga masih lebih mulia daripada yang marahnya bikin geger sekampung. Yang melepas marahnya dengan ngadu ama Raja Semesta, masih lebih mulia daripada yang menenggelamkan dirinya dalam debat atau bakuhantam.
Apa Harus Marah?
Enaknya sih ga marah. Tapi orang yang tidak marah sampai ke hati adalah orang-orang yang hatinya udah ga ada hubungannya lagi ama keduaniwian. Orang yang tidak bisa marah udah ga butuh dunia untuk makan dan hidup. Cukup menghirup sari dupa dan meditasi aja seperti demit. Hohoho.
Sementara umumnya manusia masih memacul di ladangnya masing-masing, masih berusaha melindungi sumber penghidupannya. Kalau ga dilindungi, gimana dia bisa hidup, kan?
Tapi ya itu dia tadi, cara kita melindungi ladang kita (dengan marah atau tidak, kalaupun dengan marah; marah yang semerusak apa), yang membedakan kemuliaan satu petani dengan lainnya.
Mandilah biar ga marah
Mungkin karena itu semua jalan spiritual mulainya dengan mandi dan membersihkan badan.
Logikanya mungkin begini:
Mandi = dingin = hati yang panas jadi adem.
Jadi kalau ada yang sering marah, mungkin karena dia jarang mandi. Hohoho.
Serius nih, menjaga kebersihan, selain sehat juga ngerem nafsu marah kita. Biar kalau marah, nafsu kita tidak bikin rusak antar-hubungan kita dengan diri maupun penghuni semesta lainnya. Biar kalau sampai khilaf/salah karena marah, masih ada celah untuk maaf dan perbaikan.
Karena yang sial sesial-sialnya bukan orang yang tidak pernah salah/marah, tapi mereka yang tidak belajar dari kesalahan/kemarahannya.
Atau mereka yang jarang mandi. Hohoho.
Malam terakhir. Setelah sesi terakhir, Xifu manggil. Wawancara yang cuma dihadiri Beliau & para Pelayan Dhamma. Ga ada murid lain.
Mba keringet dingin; mencium gelagat mau diomeli.; “Ini pasti gara-gara ga bisa pol “Diam Diri Mulia” selama 10 hari.”
Tapi ternyata malah ditanya soal sorban. “Kenapa kalau meditasi kamu selalu menutupi mata dengan sorban, bukannya merem saja seperti yang lain?”
Mba ngelak,“Karena saya suka melamun kalau merem biasa?”
Xifu maksa, “Karena kalau kamu mejamkan mata, you see funny things?”
Mba nyengir. “Lu yang ngomong ya, Fu?”
“Kenapa ga bilang-bilang BAHWA KAMU BISA LIHAT MAHLUK HALUS? Apa kamu pikir saya ga bakal mengerti? Lihat apa aja selama di sini?”
Mba lihat banyak, bu. Tapi yang mba ceritain ke Xifu cuma yang penting. “Ada yang minta ikut pulang ke Jatibarang.”
“And you accepted?”
“He asked nicely.”Mba nahan tawa ngeliat muka Xifu yang kesel merasa dipermainkan.
“Kenapa ga ditolak?”
“You want him back?”
Xifu nggeleng; keabisan bahan. Jadi mba cerita yang lain:
“Seorang Biksu datang, nempelin setan kecil di bahu saya. Saya berusaha melepaskannya. Tapi Biksu itu bilang, Ya, meditasi adalah belajar tidak terpengaruhi dunia luar. Baik yang halus maupun yang kasar. Dan ketika saya kembali pasrah, setan kecil itupun lepas sendiri, kecewa karena gagal menggoda.”
Xifu kelihatan lebih lega. Karena dari latihan 10-hari, ga cuma setan yang terbawa, tapi juga satu-dua tunas dhamma.
Katanya sambil nepuk jidat mba, “You’re so young, and too gifted. What you need is wisdom.”
“Wah, Fu, kalo ada yang jualan, saya juga mau yang kiloan.”
“I know,” katanya dengan penyesalan. “If only I could install you some.”
Mba kasihan ama Xifu; Beliau pengen mbantu tapi ga tau gimana. Jadi mba bilang, “Fu, meditasi memang bikin indera lebih tajam, dan akal sehat dipertanyakan. Tapi juga bikin hati lebih kokoh menghadapi yang halus-ringan maupun yang tidak.”
Buktinya, besoknya, sebelum pulang, tugas ngosek kamar mandi mba jalanin sambil nyanyi-nyanyi. Dan, baik Xifu maupun ibu dapat lagi cerita dari ruang hening penuh arti.
PS. Sakit yang kemarin udah mendingan kok, bu.
Jadi, bu, selama hampir 11 hari mba ngilang di gunung Geulis untuk latihan meditasi.
Ceritanya, di sana, tiap hari bangun jam 4 pagi, meditasi selama hampir 10-11 jam, sesekali diselang-seling makan & aktifitas lain, sampai tidur lagi jam 9:30.
Kalau ibu nanya, apa rasanya mba "mendapatkan" satu-dua yang penting dari sana, terus apa rasanya dengan meditasi ada BEBERAPA hal ruwet yang terselesaikan, dan apa jalan dari dunia luar ke kamar pribadi Tuhan dalam diri kita jadi lebih SEDIKIT lebih pendek...
Then, yes, the answer is a deep, quiet nod, mom. Ada hal-hal yang Timekeeper ga bisa ajarin. (saking tololnya mba, bukan karena beliau ga usaha). Beberapa poin penting yang mba dapat HANYA lewat meditasi 10-11 jam perhari.
Tapi ada juga kehilangan besar. Kehilangan ini terjadi karena sebelum pulang kemarin, bu, banyak teman2 seperguruan yang muji mba. Baik yang muda maupun yang sepuh.
Kata mereka, "Kamu baru pertama kali ikut latihan meditasi? Hebat; selama meditasi postur tubuhmu ga berubah, bahkan Xifu (guru) terlihat puas, semangat belajarmu besar sekali."
Mba cengar-cengir. Besar kepala. Belum tau dosa terbesar dari semua siswa adalah merasa puas diri. Karena itu...
Pagi ini, pas mandi, setelah semalaman tidur miring saking perih, dan sambil ketawa pasrah sekaligus lega karena merasa kena marah, mba ngumumin ke ibu bahwa mulai hari ini mba resmi punya ambeien ...
Di perjalanan ke Jakarta, otakku mengerut. Kram. Seandainya mulai besok ga bisa online selama 10 hari, artinya si Hning kudu diisi dengan tulisan terjadwal secukupnya. Paling ga biar ga ketara banget malesnya.
Tapi merasa harus ngarang malah bikin tambah macet. Udah bakat cuma segini-gininya, pake ditambah tegang deadline; makin keliatan aslinya.
Setengah putus asa, aku ngeluarin netbook. Barangkali menelanjangi layar bisa mengundang birahi para peri.
Yang ada, bocah di kursi seberang malah terpesona dengan mainan di pangkuanku. Anak itu duduk sejajar dengan ibu dan adiknya. Umurnya sekitar tujuh tahun, adiknya mungkin dua-belas tahun (cerewet gila!).
Aku makin gugup diperhatikan; tidak terlalu suka anak-anak, tapi juga tahu kekuasaan mereka terhadap yang lebih tua.
Anak tadi turun dari kursinya, menyeberang gang antara kursi sambil menyeret adiknya, lalu berhenti tepat di sebelahku. Asli. Nempel. Sambil melongo, perut mereka melesak tertekan sikuku.
Aku mengeluh dalam hati, menghitung kesengsaraan. “Deadline,10 hari absen, 7 hari tanpa ide, 3 draft sampah, ngantuk DAN dipelototi anak orang…Becanda kali ya?”
Nyerah deh.
Netbook aku tutup. Gantinya aku keluarin buku tulis dan pinsil. Mulai menghitung garis halaman. Awalnya lancar, “satu, dua, tiga…” lalu mulai lupa…”uhm…eeenaammm…tuuujjuuuh…eh, mas, abisnya tujuh apa ya?”
Si mas tersentak. Dia menggeleng dan tersenyum malu-malu. Adiknya yang menjawab, “delapan!”
Terus?
“Sembilan!” kata mereka barengan. Cairlah kemalu-maluan.
Saat garis di halaman itu habis dihitung. “Yak, terima kasih. Untung kalian hafal. Sekarang, coba tebak ini gambar apa?” Aku membuka buku gambar yang isinya corat-coret manic-depresif.
Itu kucing…itu anjing…itu marah. Mereka menggeleng saat melihat ekspresi takut, dan kupu-kupu. Mungkin karena belum mengenal kedua hal tadi. Atau kupukupuku mirip coro.
“PINTAR!” aku bertepuk tangan. “Mau coba nggambar?”
Serentak keduanya menggeleng kenceng.
“Bagus.” Aku merobek dua lembar kertas kosong, memilih pinsil dan pena (“Hapusannya mana?” - “Oh, maaf.”), lalu kita bertiga terpekur dengan halaman kosong masing-masing.
Jovan menggambar Goro dari Mortal Kombat, lengkap dengan guratan otot perutnya dan keempat tangannya. Ica, adiknya yang lebih galak, menggambar kedua temannya: Salsa & Kirana. Lengkap dengan gigi geripis dan kepang sekolah Katolik.
Giliranku memamerkan hasil karya: 3 halaman tulisan, tak bergambar.
“Itu apa?”
“Ini dongeng. Tentang seorang anak laki-laki yang tertarik melihat netbook, lalu mendekati yang punya netbook lalu membantunya berhitung, lalu…kenapa? Nggak bagus?”
Mukanya lucu banget: nyaris robek dengan senyum, mata menyipit, melebar, lalu hilang di balik tangan dan tawanya.
Aku puas. Periku kembali. Dongengku dibeli. Hning boleh masuk kandang. Cerita ini untuk Artha Lintang.
Stop, I want to tell you.
Stop trying to be happy. Stop wishing for happiness. Please, stop. Stop making things and people and every other things responsible for your happiness.
That’s what every religion and faith is trying to teach you. Acceptance. Keikhlasan. الإيمان بالقدر خيره و شره
You’ve had a great life. You’ve made the choices you believed in. You are loved. Everything that did not happen doesn’t matter.
No, really, they don’t.
What matters is now.
Be happy. Now.
Old folks are nostalgic obsessive compulsive memory hoarders. We gather trinkets and receipts and movie tickets. We laminate letters, frame pictures and rarely delete text messages.
That’s how we end up with a roomful of absent friends!
So we rattle and sieve and sort them. Not to discard any, but make more room for more. Just in case.
Rearranging our old friends, we end up with three categories:
There’s this set of old friends whom we take for granted to trust. We exchanged vows or friendship rings. Situation just brought us together. And situation set us apart too. We separated amicably, and had very little conflicts of interest, beside the shared domesticity and heart-to-heart conversations.
Nowadays, anytime we start a conversation with this set of friends, it’s as if we never separated. Time and space has lost its power over our relationship. Because the soul is permanent, and there is a permanent home for this friend in our hearts.
Bless this friendship.
Then there’s this set of old friends whom we knew very well but not THAT well. We know about most of their better sides. We don’t mind the hangups that we’re aware of.
Nowadays, we are comforted with maybe: We long to meet and converse again. And we procrastinate because we’re afraid that, by meeting, some of that magical idealism would break into reality. So we settle with “we’ll see” and whatifs. For the time being.
Tread carefully here.
And then there’s this set of friends who have burned than we bargained for. They make up the sorest of unrealized dreams. (Which was it, money or sex?) Whatever the past between us, long or brief, we can’t bear their presence without that tinge of discomfort and unnamable WHATIFs.
Nowadays, they fill our most absurd fantasies. Unredeemable no matter how much time and space have passed, we know that there is more harm than good in indulging those fantasies.
Don’t go there.
…jadi Cina di Glodok, tahun ‘98?
…jadi Madura di Sampit?
…jadi beragama Kristen/Islam di Poso?
…jadi melihat keluarga sendiri disembelihi di perang Paderi?
…jadi raja Hindu yang digusur agama baru sampai ke Bali?
…tumbuh-kembang tak pernah mengetahui rasanya jadi bangsa yang tertekan? Beruntung karena selamat, apa sial karena lupa?
Margi pernah mengeluh di blognya tentang kecinaannya yang nanggung. Kalau di radio Elshinta, rasanya hampir tidak pernah kita mendengar istilah CINA. Biasanya diperhalus: “warga keturunan”, China (baca: cay-na), Chinese atau Tiongkok.
Mungkin padanan Saudinya adalah sebutan “Hindi” atau “Jawa”; sama perihnya seperti disebut “Cina” di Indonesia.
Tapi semua itu sih belom apa2. Bayangin orang yang asal-usulnya campur aduk: Madura, Sunda, Batak, Arab, Padang, dst. Di setiap desa homogen, orang dengan keturunan campur-aduk harus tebal muka, karena setiap sudut mukanya bisa dihina.
Itu kalau dipanggil menurut ras memang terasa menghina.
Karena bahasa (baik itu humor, ejekan maupun pujian) sangat kontekstual: tergantung siapa yang lempar-terima. Soalnya, kalau kita tersinggung dengan sebutan yang ditempelkan, baik itu berunsur SARA, IQ atau merek pakaian, yang reaksi kita mencerminkan kepercayaan diri kita sendiri.
Misalnya kita merasa terhina dengan sebutan tolol, ya artinya kita mengakui kebenaran sebutan itu. Jika merasa tersanjung saat dibilang mirip Bule atau cerdas, ya artinya identitas kita tergantung apa kata orang.
Makanya, jadilah seperti garam, dipuji atau dihina, tetap asin. Makanya peganganlah ama motto ini: Pantang dipuji, kebal dihina, bung.
Cina ya Cina. Jawa ya Jawa. Botak ya botak. Yang penting kan tetap asin.
PS: Umumnya manusia, tak sayang karena tak kenal.
Si penggores iman pernah bilang, jin bertanduk itu kagak ada!!
Masalahnya, kalau saya bilang ke dia, "Sini deh bung, ada caranya untuk melihat jin bertanduk itu, asal sampean mau ngeliatnya. Mau?"
Keruan, orang-orang seperti dia bakalan ngetawain saya rame-rame, ngatain saya absurd & harus cepat-cepat didaftarin ke RSJ. Saya bisa (berusaha) membela diri dengan bilang, bahwa yang melihat jin bukan cuma satu dua orang saja.
Dan dengan gampang dia bisa bilang, itu namanya histeria massal!!
===Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ===
Contoh lainnya, waktu Lia Aminuddin menerima tugas nubuat, kita beramai-ramai mengatai mereka gila (oh, ya, termasuk saya). Padahal, kebanyakan anggota Salamullah yang cerdas & berwawasan luas justru mengasihani kita -- yang sok pintar dengan keyakinan kita masing2.
Saya dekat dengan salah satu anggotanya (dari sebelum dia masuk sekte itu), pernah menghadiri sidangnya di Jl.MalGajahMada, pernah cengar-cengir waktu digunjingi wartawan "Kasian deh si neng itu, cakep tapi sesat."
Seandainya lalu saya teriak2 membela diri: "Nggak kok! Saya pemeluk AgamaFulan tulen, saya di jalan yang benar!" -- yang ada hubungan saya dengan teman saya itu akan baret, dan telinga saya akan berdarah diceramahi. Haha.
===Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ===
Alkisah, Sang Buddha, waktu pulang dari meditasi yang mengantarkan pencerahan kepadanya mikir, "Beginian kagak bisa diajarin."
GusDur pun pernah bilang bahwa, agama tidak perlu dibela. Tuhan tidak butuh pembelaan. Nabi yang selama masa tugasnya dikatai gila, penipu, tukang sihir dsb, tidak butuh pembelaan kita hare gene.
Karena mau dikatai apapun, yang benar ya benar. Mau percaya atau tidak, garam akan tetap asin. Tidak butuh pembelaan atau pembuktian.
Cukup kita yang mau mencobanya sendiri atau tidak.
Cukup kita nanya sama diri sendiri: kita ini nyarinya pencerahan macam & untuk apa?
Ben memperhalusnya dalam kalimat: Terlalu terpaku dalam kepala sendiri. Tidak bisa menghadapai lebih dari satu orang setiap kali pertemuan. Intinya sih sama: Kurang Pergaulan, alias KuPer.
Salam kenal, pembaca, penulis blog ini adalah manusia yang sangat kuper. Nerdy. Seperti petasan di SPBU; tidak ada yang bisa memperkirakan kapan percikannya akan menyulut kebakaran.
Makanya, semakin sadar diri (a.k.a. paranoid), semakin malas pula bergaul dengan orang asing. Apalagi untuk sekedar basa-basi. Resiko tak sebanding dengan usaha, man. Resiko untuk mempermalukan diri sendiri di depan khayalak terlalu besar dibanding tidur nyenyak tak resah: “Aku tadi salah omong apa ya?”
Terus, mau diapain cacat sosial ini?
Ada tiga pilihan:
Halah…Gini aja kok repot sih?
Aku senang hidup dalam kepalaku. Selama cacat sosial tersebut masih bisa diakalin dengan sembunyi terus, kenapa tidak?
Ya, ya, ada saatnya aku akan terpaksa menghadapi masyarakat. Dan saat itu terjadi, akan ada orang2 seperti Ben yang dengan penuh kasihan dan kasih sayang mengingatkan: “Tangan yang diulurkan itu untuk dijabat, Neng.”
Mari berbalas kunjungan dengan Tuhan. Tuhan ke rumah kita, kita ke rumahNya.
Rumah Tuhan sih jelas² apik. Saban ke sana rasanya betah-krasan. Adem-anyem. Rumah Tuhan lapang lega, semua orang muat, semua amal tercatat, semua suguhan maknyus.
Rumah kita? Waduh, malunya.
Padahal Tuhan ingin berkunjung. Untuk menghormati kunjungan kita ke RumahNya. Untuk menilik, apa kabar ciptaan di rumahnya. Tapi rumah kita kecil, sempit,. Gentengnya bocor, ubinnya retak, debunya numpuk.
Suatu hari, karena kelamaan ga diundang² juga ke rumah kita, Tuhan nitip telegram lewat hujan & banjir. “Sop, lu masih inget Gue ga sih? Masih sayang Gue ga sih?”
Sambil nimba air yang masuk ke dalam rumah, kita balas telegram Tuhan. “Han, rumahku lagi acak adul gini. Masih mau ke sini?”
Tuhan pun datang, “Lagi acak adul aja Aku datang, apalagi kalau lagi rapi resik. Aku dimana kamu memanggilKu.”
Mencari. Tuhan. Istilah itu rasanya aneh banget.
Perlukah kita mencari Tuhan? Bukankah Tuhan nggak kemana-mana? Bukankah Tuhan ga perlu dicari?
Karena Tuhan ada di sini, dimana kita rela bersujud, serah diri.
Kenapa sampai harus dicari di buku, di agama, di Mekkah & Yerusalem? Kenapa kita kesulitan menata jadwal untuk bertemu denganNya?
Kecuali…Jangan-jangan tuhanmu bukan Tuhan beneran sampai harus dicari-cari seperti pacar, HP dan rejeki.
Uff!!
Mau ngapain kerja NGO? Semua duit yang berputar di NGO international datangnya dari umat gereja.
Yah, bapak pendidikannya cuma sampai agama Islam aja sih.
Katolik itu ngaco, tau! Mereka mengira dengan membayar uskup aja bisa beli tempat di surga.
Apa bedanya dengan konsep Zakat dan sedekah? Intinya kan sama: usaha membeli restu Tuhan.
Jadi kamu mau masuk agama mereka?
Jauh dari itu. Makin yakin dengan Islam, tapi juga memaklumi (dimana dan bagaimana) inti dari semua agama itu sama. Tuhan kita satu, Pak.
Kamu terlalu banyak mempelajari yang tidak penting!
Ye, bapak ngajarinnya sambil marah-marah. Siapa juga penasaran: Apa iya, segitunya?
In the years spent living in Indonesia, the hardest question I'm yet faced with is this: "Why would you choose to live in Indonesia?"
Whether it is asked by Saudis, Indonesians, or any other nationality, (and maybe I’m too sensitive about it,) but my ears always catch a derogatory tone in their curiosity.
When I ask them why they want to know, I often hear these assumptions:
I could’ve told them that I like getting on my bicycle every morning for coffee and quick errands. I could've told them that I like taking pictures and write in Indonesia. I could’ve tried explaining about the absence of anger. Or the abundance of kretek cigarettes. Or the smell of damp Indonesian grass; if grass could have a nationality.
What I really want to say is that, “I'm here because I have to; I love this place.”
Actually, if those answers fail to satisfy, then nothing would. But it still breaks my heart every time; because I feel like I’m doing this love much injustice by failing to answer properly. It really does.
If you were in my shoes, what would you have said?
When the job was assigned to him, the angel of death wept. "Lord, this is a tough job."
The Lord said, "Dying is not an end to living. Dying is a relief. Dying is an act of worship. Your job is to help them actualize that ultimate act of worship."
And the angel toughened up and went back doing his noble job.
You know how we question our choices only when it’s too late?
After asking the Timekeeper about accepting the world as it is, I risked getting severely offended by asking him, “Are you saying that my life in Indonesia is defying gravity? That MY UNCONVENTIONAL LIFE HERE HAS BEEN NOTHING BUT AN EGO OVERDRIVE?”
“Absolutely, because you talk without the walk.” *laughing pause* “Nawh, I’m just kidding. Get off the floor. I get my kicks whenever you doubt yourself like this.”
Bless them elders who know exactly how make you feel stupid without saying so.
“Look at your basic needs. Before intimacy and love, before needs of self-actualization can be fulfilled, you must feel safe and secure. You didn’t have that in your old life. It’s not just the ego that made you fight for your unconventional life. It was the natural next step.”
If anything could prove his point, I look at my writings. I mean, haven’t I been better at talking about needs beyond security and safety since I repatriated?
PS: No, Ben, I’m not referring your deadlines.
Aku bilang bahwa aku lebih sayang ama Timekeeper.
Dia bilang, “Gapapa.”
…bahwa aku ga bisa masak, agak autis dan ADD.
Dia bilang, “Gapapa.”
…bahwa aku berantakan dan takut mandi.
Dia sempat tersendat ragu sesaat, tapi akhirnya bilang…”Gapapa juga.”
Sekali-kali aku pengen nanya ama dia, ARE YOU OUT OF YOUR MIND?
Segitunyakah?
Tapi, well, biarpun otaknya salah belah, it’s in my favorite color, man.
Waktu kecil, kalo ibu mendengar Ade atau Anggi nangis, pasti langsung teriak: “Yayaaaaaaa…usap-usap adiknya!”
Ga peduli apa dia menangis karena lompat dari atas lemari atau karena belajar sunat sendiri, pokoknya yang pertama diteriaki ibu ya mbak Yaya. Emang sih, Ade pernah pitak-pitak karena Yaya sisirin. Anggi juga pernah ga bisa tidur siang & nangis seharian karena gulingnya Yaya buang ke tempat sampah. Dua kali.
Tapi abis itu GA LAGI KOK!
Anyways, job desk sebagai anak paling tua, selain langganan menyiksa adik, juga jadi agen hiburan mereka. Seperti yang ibu teriakin itu, kalau adiknya nangis kudu ikhlas disalahin. Kalau adiknya nangis kudu dibujukin, diusap-usap & dibekep dalam sumur dicium sampai diam.
Sialnya, kebiasaan² itu kebawa sampe gede.
Sampe gede juga tetep kepikiran gimana caranya menghibur adik. Meskipun (rasanya) makin tua tugas jadi kakak jadi makin nyebelin.
Nyebelinnya; karena sekarang, yang niatnya mau ngehibur, malah jadi ribet. Niatnya mau nyenengin, malah jadi berantem. Kalau dulu ditepuk² aja bokongnya udah meneng, sekarang malah makin sewot. Kalau dulu dikrecekin mainan udah lupa, sekarang dikipasin majalah pria...ihh, Yaya yang males megangnya!
*manyun*
Ben pernah cerita tentang John Hopkins. Salah satu latihannya berupa katarsis massal: rem emosi dikosongin ampe blong, terus dimuntahkan semua. Berikut borok, lendir dan nanahnya. (Ga kebayang gimana rasanya jadi obyek latihan seperti itu.)
Yaya nyebutnya kentut. Soalnya marah seperti kentut; kalau ditahan malah bikin sakit perut. Marah yang disalurkan rasanya seperti api di pabrik kertas: Merembet kemana², tapi semisal bahan bakarnya abis, atau tiba² hujan, ya sudah. Byar-Pet.
*mikir*
Emang mestinya begitu ya? Daripada berusaha ngebujukin, mending didiamkan aja. Biar saja mereka puas²in nangis & marah² sendiri. Daripada jadi budek atau ikutan gedek.
Atau, minimal, diamkan sampai nangis. Karena kalau saat dia sudah nangis, mengusap-usap dirinya juga lebih sayang. Kapanpun dia mulai nangis. Secara, antara kakak-adik kan wudhunya 'kan tidak batal. Jadi bisa meluk, mencium, ngusap-ngusap kapan aja dia siap menerimanya. Sampai kapalan. Sampai saling memberi kesaksian di Hari Nanti.
Amin.
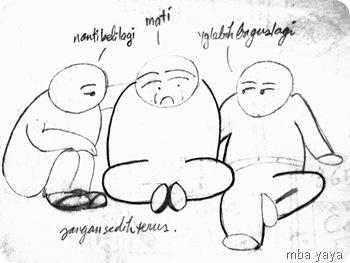
Itu namamu.
Dari kata benedict. Atau Big Ben. Atau putra, dalam bahasa Ibrani & Arab.
Seandainya dikasih, aku pengen menamai anak dengan nama itu. Tapi untuk sementara, kamu boleh pinjam.
Biar nggak lupa. I've the memory of fish, you know?Kata Ben, semua cerita-ceritaku bermuara di sebaris kalimat.
Kata Ben, sebaris kata itu sudah ada sejak kali pertama aku (kembali telaten) mencatati wahyu.
Mungkin karena kalimat sebaris itu wahyu pertama. Seperti “Let there be light.” Atau, “إقرأ.” Atau, “Saya terima nikahnya.”
Atau karena kalimat itu lahir saat halaman maupun penulisnya sedang kosong sekosong-kosongnya, sampai gemanya lancar mencapai ribuan kalimat berikutnya. Lalu membingkai semuanya dalam angguk mafhum terselubung.
Karena, bagi pencatatnya, kalimat sebaris itu adalah cahaya asal sejak mati terakhir, dan suara pertama setelah lama hening, dan awal kepasrahan setelah lama melawan.
“Yang dikasih diterima. Yang tidak jangan diminta.”
PS: Mungking blog sampingan ini perlu ganti nama: www.kata.ben.com -- *muntah* -- Okay, sorry, ga jadi.
Malam Jumat kemarin, saat sholat Isha, aku berdoa. Konten doanya bukan mau memilih antara A atau B. Juga bukan meminta sesuatu dariNya. Kont...